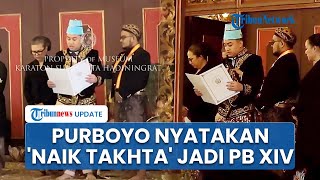Citizen Journalism
AZA, Teman dan Sahabat Tionghoa Sejak 1950-an, Para Tukang yang Sukses Jadi Pengusaha
Ketika pecah perang PRRI pada tahun 1958, gedung sekolah Tionghoa itu berikut gedung sekolah-sekolah negeri lainnya habis terbakar.
Dengan Christianto Wibisono, Tionghoa asal Semarang yang sejak mahasiswa sudah jadi wartawan itu saya cukup akbrab, sama-sama alumni UI dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia.
Melly G Tan adalah dosen saya di UI.
Ketika mahasiswa, beliau membimbing saya untuk sejumlah penelitian yang berkaitan dengan masalah Tionghoa.
Bahkan skripsi saya yang diterbitkan majalah PRISMA edisi Indonesia dan edisi bahasa Inggris juga tentang asimilasi Tionghoa di Indonesia.
Sesuatu yang hingga saat ini tetap berpotensi menjadi problem sosial, terutama karena adanya jurang ekonomi yang semakin melebar.
Berbagai usaha sejak awal kemerdekaan sudah dilakukan pemerintah.
Sebut saja Program Benteng yang diberlakukan sejak tahun 1950, suatu keberpihakan terbuka terhadap pengusaha pribumi dalam hal impor.
Pada periode Eknomi Terpimpin era Soekarno, terbit Peraturan Presiden yang dikenal sebagai PP 10, membatasi gerak warga Tionghoa berdagang eceren.
PP 10 itu menimbulkan protes keras pemerintahan Republik Rakyat China (RRC), tapi pemerintah Indonesia bergeming.
Dampaknya terjadi eksodus pulang kampung puluhan ribu warga Tionghoa ke negeri leluhurnya.
Pemerintahan Orde Baru mencoba pendekatan baru.
Pendekatan sosiologis melalui program asimilasi atau pembauran.
Dimulai dengan penggantian nama, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Boleh nama Jawa atau nama Islami seperti dua orang Yasin yang saya kenal di atas.
Bersamaan dengan memburuknya hubungan RI-RRC karena RRC dianggap terlibat kudeta G30S-PKI, sekolah-sekolah Tionghoa dibubarkan, aksara China dilarang dan ruang gerak kalangan Tionghoa di lingkungan pemerintahan dibatasi.
Akibatnya aktivitas mereka terkonsentrasi di dunia bisnis.
Mereka yang awalnya sejak zaman kolonial berposisi sebagai pedagang perantara, mulai mendominasi sektor perdagangan.
Setelah rusuh Malari 1974, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pribumi melalui pemberian kredit KIK/KNKP.
Dan ketika liberalisasi perbankan tahun 80an, ketimpangan ekonomi semakin terasa.
Dengan dibukanya izin mendirikan bank, pengusaha Tionghoa sudah masuk ke seluruh sektor ekonomi.
Bukan saja di perdagangan, tetapi juga sektor industri dan jasa serta perbankan. BLBI, Obligasi Rekap dan restruturiasi perbankan oleh BPPN , bukan saja berdampak ekonomi, tetapi juga sosial karena faktanya ketimpangan semakin luas dan dalam pascakrisis ekonomi dan era reformasi.
Presiden Jokowi bukannya tidak ada perhatian terhadap masalah ketimpangan ini. Bahkan sudah pernah dibentuk tim dengan ketuanya Menko Perekonomian Darmin Nasution, beberapa waktu setelah Aksi 212 yang ditenggarai bukan semata masalah agama, tetapi lebih bersumber dari masalah ketimpangan kehidupan ekonomi.
Sayangnya, sampai berakhirnya masa jabatan Darmin, tim yang tujuannya menghasilkan suatu kebijakan keberpihakan terbuka terhadap pribumi—mirip “new economic policy” yang pernah diterapkan Malaysia, tak terwujud.
Masalah ketimpangan tersebut tentulah menjadi masalah dan beban pikiran kita bersama. Khususnya dalam suasana Tahun Baru Imlek saat ini.
Termasuk oleh teman-teman dan para sahabat Tionghoa saya. Gong Xi Fa Cai (yang artinya: Selamat Berbahagia dan Kaya Raya). Tentulah yang terbaik, adalah kaya raya bersama (jika mungkin). (*)
*Antony Zeidra Abidin (AZA), mantan Wakil Gubernur Jambi
• Berhasil Pulang Saat Kota Wuhan Diisolasi karena Virus Corona, Begini Cerita Mahasiswa Hasan Hidayat
• Korban Meninggal Akibat Virus Corona 106 Jiwa, 4500 Orang Terinfeksi, WNI Ungkap Kondisi di Wuhan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/antony-zeidra-abidin-aza-mantan-wakil-gubernur-jambi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/27102025-Mochammad-Farisi.jpg)