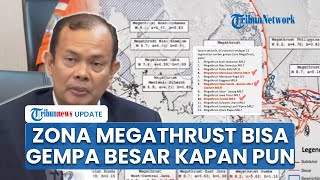Citizen Journalism
AZA, Teman dan Sahabat Tionghoa Sejak 1950-an, Para Tukang yang Sukses Jadi Pengusaha
Ketika pecah perang PRRI pada tahun 1958, gedung sekolah Tionghoa itu berikut gedung sekolah-sekolah negeri lainnya habis terbakar.
*oleh Antony Zeidra Abidin (AZA)
DI BUKIT di depan rumah saya di Kota Bangko, ibukota Kabupaten Merangin pada akhir tahun 50-an, terdapat sebuat sekolah Tionghoa.
Tangga beton di lereng menuju sekolah itu, terletak di seberang jalan rumah keluarga kami.
Kepala sekolah dan istrinya, sering bertegur sapa dengan keluarga kami.
Puluhan murid-muridnya, adalah anak para pedagang kelontong, tukang gigi, tukang emas, tukang foto atau pemilik studio foto, pemilik bengkel sepeda, pemilik pabrik kopi rumahan, warung kopi.
Tidak ada pedagang rempah-rempah atau toko tekstil, karena bisnis ini pada saat itu menjadi sepesialisasi etnik India.
• Warga Tionghoa Asal Jambi Hendra Kho Jadi Anggota Sat Bravo 90, Pasukan Elite TNI AU
• Pengusaha Tionghoa Sumbangkan Alquran Raksasa dari Sulaman, Mushaf 17 Meter
Pendatang dari India itu, umumnya menikah dengan wanita setempat. Mereka beragama Islam.
Ketika pecah perang PRRI pada tahun 1958, gedung sekolah Tionghoa itu berikut gedung sekolah-sekolah negeri lainnya habis terbakar.
Banyak gedung pemerintah dan juga pembangkit listrik yang terbakar.
Akibatnya, banyak yang mengungsi, termasuk keluarga kami yang ketika itu pindah untuk sementara ke kota Jambi.
Sekembali kami dari pengungsian pada tahun 1959, suasana Bangko terasa sangat sepi.
Gedung perkantoran dan sekolah yang terbakar masih tetap menjadi puing. Belum dibangun. Termasuk sokolah Tionghoa itu.
Gedung Sekolah Rakyat (SR), tempat dulu saya sekolah juga masih berupa onggokan puing, tetapi tak lama kemudian dibangun SR (sekarang SD) di bekas perkantoran kabupaten di pusat kota.
Sedangkan sekolah Tionghoa Bangko itu, tak pernah dibangun lagi, hingga sekarang.
Pasalnya, saat itu terbit Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA berdagang eceren di kota kecamatan. Sedangkan ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo dan Kota Bangko yang hancur lebur itu turun status menjadi ibukota kecamatan.
Warga Tionghoa pedagang eceran berstatus warga negara asing, hengkang.

Yang tersisa hanya beberapa keluarga: Aliong (tukang gigi), Angau (tukang emas), Athiu (bengkel sepeda), Cincu (ukang foto), Lak Khun (pabrik kopi rumahan), Atang (warung kopi), Apong (tukang gigi).
Tak satu pun pedagang eceran.
Yang menarik, keluarga Tionghoa yang pada awalnya adalah “para tukang” tersebut, umumnya beralih profesi menjadi pengusaha, dan sukses di berbagai bidang.
Misalnya keluarga Aliong yang tadinya tukang gigi itu, kini adalah pengusaha kaya yang memiliki lahan sawit puluhan ribu hektare.
Anak Athui, kini memiliki toko besar berjualan aksoseri mobil di pusat Kota Jambi.
Ada juga yang menjadi pengusaha perkapanlan yang cukup maju, yang banyak menampung warga Bangko non-Tionghoa di perusahaannya.
Sampai saat ini, saya masih bergaui akrab dengan keluarga Aliong dan Athui. Mereka adalah sahabat saya “sekampung” asal kota Bangko.
Pada awal Orde Baru, saya sekolah ke Kota Jambi.
SMP Negeri 4 tempat saya sekolah, adalah eks sekolah Tionghoa.
Sejak peristiwa G 30 S, hubungan RI-China memburuk.
Dampaknya sekolah-sekolah Tionghioa itu tutup dan gedungnya kemudan dipakai oleh sekolah negeri sore yang sebelumnya menggunakan gedung sekolah negeri “edisi” pagi.
Seingat saya, di sekolah negeri itu tak ada murid Tionghoa Jambi.
Mereka pindah ke sekolah Katolik atau ke kota lain.
Kemudian ada seorang siswa Tionghoa, pindahan dari Brebes, tetapi dia lebih menonjol Jawanya, medok dan halus tutur bahasanya.
Tentu saja kami sekelas akrab dengan Tionghoa Jawa yang sering ngajak makan rujak di rumahnya ini.
M Yasin, adalah seorang Tionghoa, anak angkat mantan Gubernur Jambi.

Saya kenal sewaktu dalam perjalanan saya naik kapal laut dari Jambi ke Jakarta tahun 1967.
Dia tahu saya pertama kali ke Jakarta, kemudian mengantarkan saya ke rumah kakak saya di Kebon Sirih yang berjarak hanya beberapa puluh meter dari rumah bapak angkatnya itu.
Yasin, sahabat saya itu, kini menetap di Jambi sebagai pengusaha cukup sukses.
Di kesempatan lainnya pada tahun 90an, dalam perjalanan ke Eropa, saya juga mengenal seorang tua yang juga bernama Yasin.
Nama yang sangat religius dan banyak dibaca pada acara “Yasinan” pada acara-acara tertentu, terutama saat ada yang meninggal.
Tetapi Tionghoa tua asal Palembang ini, bukanlah seorang muslim.
Tionghoa lainnya yang dulunya biasa dipanggil Abi, ketika ganti nama pada awal Orde Baru, memilih nama ayah saya: Abidin. Sesuatu yang biasa di beberapa daerah Sumatera.
Selama lebih dari setengah abad saya tinggal di Jakarta, teman dan sahabat Tionghoa saya sangat banyak.
Tetangga saya, di sebelah dan di depan rumah saya sejak dulu selalu ada warga Tionghoanya.
Bahkan teman sekamar saya di asrama UI Daksinapati adalah seorang Tionghoa asal Surabaya yang berkarier sebagai diplomat dan pernah menjadi duta besar di beberapa negara.
Di perusahaan penerbitan saya, saya biasa mempekerjakan bidang marketing orang Tionghoa.
Di salah satu perusahaan yang saya dirikan tahun 1994, komisaris utamanya Ir Ciputra yang sampai beliau wafat Desember sebulan lalu, almarhum tetap tercatat sebagai preskomnya.
Sebagai anggota dan pengurus DPP Real Estat Indonesia, saya bergaul akrab dengan sejumlah pengusaha Tionghoa.
Beberapa di antaranya juga pernah aktif dan menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar. Antara lain Enggartiarso Lukita.
Minggu lalu saya bertemu Budiarsa, menantu Pak Ciputra, di rumah duka tempat ayahnya di semayamkan.
Dengan Christianto Wibisono, Tionghoa asal Semarang yang sejak mahasiswa sudah jadi wartawan itu saya cukup akbrab, sama-sama alumni UI dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia.
Melly G Tan adalah dosen saya di UI.
Ketika mahasiswa, beliau membimbing saya untuk sejumlah penelitian yang berkaitan dengan masalah Tionghoa.
Bahkan skripsi saya yang diterbitkan majalah PRISMA edisi Indonesia dan edisi bahasa Inggris juga tentang asimilasi Tionghoa di Indonesia.
Sesuatu yang hingga saat ini tetap berpotensi menjadi problem sosial, terutama karena adanya jurang ekonomi yang semakin melebar.
Berbagai usaha sejak awal kemerdekaan sudah dilakukan pemerintah.
Sebut saja Program Benteng yang diberlakukan sejak tahun 1950, suatu keberpihakan terbuka terhadap pengusaha pribumi dalam hal impor.
Pada periode Eknomi Terpimpin era Soekarno, terbit Peraturan Presiden yang dikenal sebagai PP 10, membatasi gerak warga Tionghoa berdagang eceren.
PP 10 itu menimbulkan protes keras pemerintahan Republik Rakyat China (RRC), tapi pemerintah Indonesia bergeming.
Dampaknya terjadi eksodus pulang kampung puluhan ribu warga Tionghoa ke negeri leluhurnya.
Pemerintahan Orde Baru mencoba pendekatan baru.
Pendekatan sosiologis melalui program asimilasi atau pembauran.
Dimulai dengan penggantian nama, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Boleh nama Jawa atau nama Islami seperti dua orang Yasin yang saya kenal di atas.
Bersamaan dengan memburuknya hubungan RI-RRC karena RRC dianggap terlibat kudeta G30S-PKI, sekolah-sekolah Tionghoa dibubarkan, aksara China dilarang dan ruang gerak kalangan Tionghoa di lingkungan pemerintahan dibatasi.
Akibatnya aktivitas mereka terkonsentrasi di dunia bisnis.
Mereka yang awalnya sejak zaman kolonial berposisi sebagai pedagang perantara, mulai mendominasi sektor perdagangan.
Setelah rusuh Malari 1974, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pribumi melalui pemberian kredit KIK/KNKP.
Dan ketika liberalisasi perbankan tahun 80an, ketimpangan ekonomi semakin terasa.
Dengan dibukanya izin mendirikan bank, pengusaha Tionghoa sudah masuk ke seluruh sektor ekonomi.
Bukan saja di perdagangan, tetapi juga sektor industri dan jasa serta perbankan. BLBI, Obligasi Rekap dan restruturiasi perbankan oleh BPPN , bukan saja berdampak ekonomi, tetapi juga sosial karena faktanya ketimpangan semakin luas dan dalam pascakrisis ekonomi dan era reformasi.
Presiden Jokowi bukannya tidak ada perhatian terhadap masalah ketimpangan ini. Bahkan sudah pernah dibentuk tim dengan ketuanya Menko Perekonomian Darmin Nasution, beberapa waktu setelah Aksi 212 yang ditenggarai bukan semata masalah agama, tetapi lebih bersumber dari masalah ketimpangan kehidupan ekonomi.
Sayangnya, sampai berakhirnya masa jabatan Darmin, tim yang tujuannya menghasilkan suatu kebijakan keberpihakan terbuka terhadap pribumi—mirip “new economic policy” yang pernah diterapkan Malaysia, tak terwujud.
Masalah ketimpangan tersebut tentulah menjadi masalah dan beban pikiran kita bersama. Khususnya dalam suasana Tahun Baru Imlek saat ini.
Termasuk oleh teman-teman dan para sahabat Tionghoa saya. Gong Xi Fa Cai (yang artinya: Selamat Berbahagia dan Kaya Raya). Tentulah yang terbaik, adalah kaya raya bersama (jika mungkin). (*)
*Antony Zeidra Abidin (AZA), mantan Wakil Gubernur Jambi
• Berhasil Pulang Saat Kota Wuhan Diisolasi karena Virus Corona, Begini Cerita Mahasiswa Hasan Hidayat
• Korban Meninggal Akibat Virus Corona 106 Jiwa, 4500 Orang Terinfeksi, WNI Ungkap Kondisi di Wuhan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/antony-zeidra-abidin-aza-mantan-wakil-gubernur-jambi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/27102025-Mochammad-Farisi.jpg)