Opini
Analisis Sentimen dan Framing Media terhadap Suku Anak Dalam atau SAD dalam Kasus Penculikan Bilqis
Pada tanggal 3 November, sentimen negatif terhadap SAD berada pada angka 25 persen, dengan mayoritas publik (65 persen) masih bersikap netral.
Analisis Sentimen dan Framing Media terhadap Suku Anak Dalam atau SAD dalam Kasus Penculikan Bilqis
Penulis: Ade Novia Maulana, M.Sc
Penulis adalah Dosen pada Prodi Jurnalistik Islam dan Prodi Sistem Informasi di UIN STS Jambi
*Periode analisis: 3-16 November 2025
PADA tanggal 2 November 2025, berita penculikan Bilqis, balita asal Makassar, mengguncang publik Indonesia. Enam hari kemudian, pada 8 November 2025, Balqis ditemukan di tengah komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Merangin, Jambi, sebelum akhirnya tiba kembali di Makassar pada 9 November 2025.
Namun, dibalik kisah penemuan yang seharusnya menjadi kabar gembira ini, muncul fenomena yang jauh lebih mengkhawatirkan: bagaimana media massa dan platform digital secara sistematis membingkai SAD sebagai pihak yang mencurigakan, terbelakang, dan bahkan eksotis dalam narasi pemberitaan mereka.
Analisis sentimen terhadap lebih dari 650 artikel berita, postingan media sosial, dan diskusi publik dari tanggal 3 hingga 16 November menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Sejak hari ketiga kasus ini mencuat, sentimen negatif terhadap SAD mengalami eskalasi yang drastis.
Pada tanggal 3 November, sentimen negatif terhadap SAD berada pada angka 25 persen, dengan mayoritas publik (65 persen) masih bersikap netral.
Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin intensifnya pemberitaan, sentimen negatif melonjak tajam mencapai 88 persen pada tanggal 8 November ketika Balqis ditemukan di lokasi SAD, sementara sentimen netral merosot drastis menjadi hanya 9 persen.

Bagian yang menarik adalah bagaimana sentimen publik mulai berubah setelah tanggal 9 November. Ketika Balqis kembali ke Makassar dan investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa tidak ada keterlibatan langsung SAD dalam penculikan, sentimen negatif mulai menurun.
Pada tanggal 11 November, terjadi titik balik di mana sentimen negatif dan positif berada pada posisi yang sama yaitu 38 persen. Setelah itu, sentimen positif terus meningkat hingga mencapai 55 persen pada tanggal 16 November, sementara sentimen negatif turun menjadi 18 persen.
Transformasi ini menunjukkan bahwa publik Indonesia sebenarnya responsif terhadap klarifikasi dan fakta, namun kerusakan terhadap citra komunitas SAD telah terjadi selama periode puncak prasangka tersebut.
Volume pemberitaan dengan framing negatif mengikuti tren serupa. Dari 22 artikel pada tanggal 3 November, jumlah publikasi yang membingkai SAD secara negatif melonjak menjadi 110 artikel pada tanggal 8 November, bertepatan dengan penemuan Balqis.
Angka ini menunjukkan bahwa media tidak hanya memberitakan fakta penemuan, tetapi secara aktif membangun narasi yang menempatkan SAD sebagai objek yang mencurigakan.

Volume pemberitaan mulai menurun secara signifikan setelah tanggal 9 November. Pada tanggal 16 November, hanya tersisa 18 artikel dengan framing negatif, menunjukkan penurunan hampir 85 persen dari puncaknya.
Namun, penurunan volume ini tidak serta-merta menghapus dampak dari ratusan artikel yang telah tersebar selama periode sebelumnya. Narasi negatif yang telah terbentuk memiliki efek jangka panjang dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap SAD.
Ketika mengkaji lebih dalam kategori framing negatif yang digunakan media sepanjang periode analisis, terungkap empat pola dominan yang secara konsisten muncul dalam pemberitaan. Framing "keterbelakangan" menjadi yang paling masif dengan akumulasi 53 artikel yang secara eksplisit atau implisit menggambarkan SAD sebagai kelompok primitif, terisolasi, dan tidak beradab.
Kategori "kecurigaan" menghasilkan 46 artikel yang membingkai keberadaan Balqis di tengah SAD sebagai indikasi keterlibatan mereka dalam penculikan, meskipun tidak ada bukti forensik yang mendukung. Framing "eksotisasi" muncul dalam 30 artikel yang memperlakukan SAD sebagai objek wisata antropologis.
Fakta yang menarik, framing "viktimisasi" yang menempatkan SAD sebagai korban diskriminasi justru mengalami peningkatan signifikan di periode akhir analisis, mencapai 35 artikel pada tanggal 16 November.

Peningkatan framing viktimisasi diperiode akhir menunjukkan adanya pergeseran narasi setelah fakta mulai terungkap. Jurnalis dan aktivis mulai menulis artikel yang membela SAD dan mengkritik prasangka yang telah terbentuk. Namun, pergeseran ini terjadi terlambat dan dengan volume yang jauh lebih kecil dibandingkan gelombang artikel negatif sebelumnya.
Grafik menunjukkan bahwa ketiga kategori negatif utama (keterbelakangan, kecurigaan, eksotisasi) mengalami lonjakan tajam hingga tanggal 8 November dan kemudian melambat, sementara viktimisasi justru terus meningkat hingga akhir periode analisis.
Indeks intensitas sentimen negatif memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang seberapa keras dan emosional narasi negatif tersebut dikonstruksi.
Pada skala 0 hingga 10, di mana 0 menunjukkan tidak ada sentimen negatif dan 10 menunjukkan sentimen negatif yang ekstrem, indeks ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dari angka 4.2 pada tanggal 3 November, intensitas meningkat secara konsisten hingga mencapai puncaknya pada angka 8.5 di tanggal 8 November.

Penurunan intensitas setelah tanggal 8 November berlangsung lebih gradual dibandingkan kenaikannya. Pada tanggal 16 November, intensitas turun menjadi 2.4, menunjukkan bahwa meskipun volume pemberitaan negatif menurun drastis, muatan emosional dalam diskusi publik masih memerlukan waktu lebih lama untuk mereda.
Angka 2.4 ini menandakan bahwa prasangka terhadap SAD belum sepenuhnya hilang, melainkan hanya berkurang intensitasnya. Bahasa yang digunakan dalam diskusi publik masih mengandung elemen kecurigaan dan stereotip, meskipun tidak seekstrem periode sebelumnya.
Perbandingan antara tone media nasional dan media lokal Jambi mengungkapkan disparitas yang signifikan dan konsisten sepanjang periode analisis.
Media nasional menunjukkan tone negatif yang jauh lebih tinggi, dimulai dari angka 3.8 pada tanggal 3 November dan mencapai puncaknya di 8.7 pada tanggal 8 November. Sebaliknya, media lokal Jambi menunjukkan tone yang relatif lebih moderat, dimulai dari 2.0 dan hanya mencapai 4.2 pada puncaknya.

Kesenjangan antara kedua kelompok media ini tetap konsisten hingga akhir periode analisis. Pada tanggal 16 November, media nasional masih menunjukkan tone negatif 2.7 sementara media lokal hanya 1.8.
Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor struktural.
Pertama, jurnalis lokal di Jambi memiliki pemahaman kontekstual yang lebih baik tentang SAD, termasuk dinamika sosial dan geografis mereka. Mereka telah berinteraksi dengan komunitas ini dalam berbagai konteks sebelumnya, sehingga tidak mudah terjebak dalam stereotip.
Kedua, media lokal memiliki akses langsung ke narasumber di lapangan, termasuk tokoh masyarakat adat, aparat setempat, dan saksi mata yang memberikan perspektif lebih berimbang.
Ketiga, media nasional cenderung menggunakan angle sensasional untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas, sementara media lokal lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang pemberitaan terhadap harmoni sosial di wilayah mereka.
Korelasi antara volume pemberitaan dan sentimen publik menunjukkan hubungan yang sangat erat sepanjang periode analisis. Setiap kenaikan volume artikel dengan framing negatif diikuti oleh peningkatan sentimen negatif publik yang hampir proporsional. Ketika volume artikel mencapai 110 pada tanggal 8 November, sentimen negatif publik juga mencapai puncaknya di 88 persen.

Hal yang menarik, penurunan sentimen negatif publik berlangsung lebih lambat dibandingkan penurunan volume pemberitaan. Pada tanggal 16 November, volume artikel turun menjadi 18 (penurunan 84 persen dari puncak) sementara sentimen negatif hanya turun menjadi 18 persen (penurunan 80 persen dari puncak).
Fenomena ini mengindikasikan bahwa efek dari narasi media memiliki inersia—prasangka yang terbentuk tidak serta-merta hilang ketika stimulus negatif berkurang. Pola ini mengonfirmasi teori agenda-setting dalam komunikasi massa, di mana media tidak hanya memberitahu publik tentang apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara memikirkannya, dan efek ini bertahan bahkan setelah intensitas pemberitaan menurun.
Distribusi platform dengan sentimen negatif menunjukkan dinamika yang konsisten di berbagai ruang digital sepanjang periode analisis. Twitter menempati posisi teratas sejak awal hingga akhir periode, mencapai puncak 92 persen konten negatif pada tanggal 8 November sebelum turun menjadi 24 persen pada tanggal 16 November. Facebook mengikuti dengan pola serupa, dari 25 persen pada tanggal 3 November menjadi 85 persen pada puncaknya, lalu turun ke 23 persen di akhir periode.

Instagram dengan 78 persen pada puncaknya menunjukkan bahwa platform visual juga tidak luput dari narasi negatif, terutama melalui caption dan komentar pada postingan terkait kasus ini. Forum online mencapai 73 persen dan portal berita 68 persen pada tanggal 8 November.
Yang mengkhawatirkan adalah kecepatan penyebaran sentimen negatif di semua platform ini—dari tingkat yang relatif rendah pada tanggal 3 November, semua platform mengalami lonjakan eksponensial dalam lima hari. Twitter yang dikenal dengan karakteristiknya yang cepat dan reaktif menjadi ruang di mana spekulasi, rumor, dan generalisasi berkembang paling pesat.
Facebook dengan algoritma grup dan komunitas memperkuat echo chamber yang memperkuat bias negatif. Meskipun semua platform menunjukkan tren penurunan setelah tanggal 9 November, pola ini tetap menunjukkan bahwa ekosistem digital Indonesia sangat rentan terhadap penyebaran prasangka kolektif dalam waktu singkat.
Fenomena yang terjadi dalam kasus Balqis ini adalah cerminan dari masalah struktural yang lebih besar dalam jurnalisme Indonesia dan literasi media publik.
Pertama, kecenderungan media untuk menggunakan framing yang sensasional demi meningkatkan engagement dan traffic, tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang terhadap kelompok minoritas seperti SAD.
Kedua, kurangnya verifikasi dan pendalaman dalam pemberitaan, di mana kecurigaan dan spekulasi diperlakukan sejajar dengan fakta yang telah terverifikasi.
Ketiga, bias kultural yang masih mengakar dalam cara media mainstream memandang komunitas adat, yang seringkali direduksi menjadi objek eksotis atau dianggap terbelakang dibandingkan masyarakat urban.
Keempat, algoritma platform media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat, termasuk kemarahan dan ketakutan, sehingga narasi negatif mendapat amplifikasi yang jauh lebih besar dibandingkan klarifikasi atau konten yang berimbang.
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang dari konstruksi narasi ini. Meskipun Balqis telah kembali dengan selamat dan investigasi tidak menemukan keterlibatan SAD dalam penculikan, stigma yang telah tertanam dalam benak publik tidak mudah dihapus.
Data menunjukkan bahwa meskipun sentimen positif melampaui sentimen negatif pada pertengahan November, tingkat kepercayaan terhadap SAD dan komunitas adat lainnya kemungkinan telah mengalami kerusakan permanen di mata sebagian masyarakat.
Komunitas SAD, yang sudah menghadapi marginalisasi sistematis dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengakuan hak atas tanah, kini harus menanggung beban tambahan berupa prasangka kolektif yang diperkuat oleh media massa dan platform digital.
Anak-anak SAD mungkin akan menghadapi diskriminasi lebih besar jika mereka memiliki akses ke pendidikan formal. Program-program pemberdayaan yang melibatkan SAD bisa mengalami resistensi dari masyarakat umum yang telah terpengaruh oleh narasi negatif. Lalu, yang paling tragis, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi cara media dan publik memperlakukan komunitas adat lainnya di Indonesia di masa depan.
Analisis periode 3-16 November ini juga mengungkapkan pola yang memprihatinkan dalam siklus berita Indonesia. Media cenderung sangat cepat dalam membangun narasi sensasional namun sangat lambat dalam memberikan klarifikasi yang memadai. Volume artikel klarifikasi dan pembelaan terhadap SAD jauh lebih kecil dibandingkan artikel yang membingkai mereka secara negatif.
Bahkan ketika framing viktimisasi mulai meningkat di akhir periode, jangkauan dan impact-nya tidak sebanding dengan gelombang prasangka sebelumnya. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang berbahaya, di mana publik jauh lebih terpapar pada narasi negatif dibandingkan koreksi atau perspektif alternatif.
Kasus Balqis seharusnya menjadi momentum refleksi bagi semua pihak. Media massa perlu mengevaluasi standar etika jurnalistik mereka, terutama dalam memberitakan kelompok minoritas dan vulnerable. Prinsip verifikasi, check and recheck, harus diterapkan secara konsisten sebelum mempublikasikan narasi yang berpotensi merugikan kelompok tertentu.
Platform digital perlu lebih proaktif dalam moderasi konten yang mengandung hate speech dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta merancang algoritma yang tidak hanya memprioritaskan engagement tetapi juga akurasi dan keseimbangan informasi.
Pendidikan literasi media bagi publik harus diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi yang mereka terima, termasuk kemampuan untuk mengenali bias, memverifikasi sumber, dan mempertanyakan narasi dominan.
Pemerintah dan Dewan Pers perlu memastikan bahwa hak-hak komunitas adat seperti SAD dilindungi, tidak hanya dari ancaman fisik tetapi juga dari kekerasan simbolik yang dilakukan melalui narasi media. Perlu ada mekanisme pemantauan dan sanksi terhadap media yang terbukti menyebarkan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga memiliki peran penting dalam melakukan counter-narrative, menyediakan informasi yang akurat dan kontekstual tentang komunitas adat, serta mengadvokasi kebijakan yang melindungi mereka dari marginalisasi dan stereotip.
Balqis telah pulang ke rumahnya dengan selamat, dan itu adalah kabar yang patut disyukuri. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: kapan SAD bisa pulang ke tempat yang seharusnya mereka tempati dalam imajinasi kolektif bangsa ini—bukan sebagai objek kecurigaan atau eksotisasi, melainkan sebagai warga negara dengan martabat dan hak yang setara?
Data menunjukkan bahwa perjalanan menuju pemulihan citra mereka masih panjang. Diperlukan upaya kolektif dari media, pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tragedi narasi yang terjadi dalam kasus Balqis tidak terulang kembali terhadap komunitas adat lainnya di Indonesia.
Sentimen positif yang mulai meningkat di akhir periode analisis memberikan secercah harapan bahwa publik Indonesia mampu belajar dari kesalahan, namun pembelajaran ini harus diterjemahkan menjadi perubahan sistemik dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi informasi tentang kelompok minoritas di negeri ini. (*)
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi
Baca juga: Jadwal Puasa Ramadhan 2026, 19 Februari Awal Puasa?
Baca juga: Kronologi Penemuan Motor di Sungai Batanghari Jambi: Berkat Air Surut dan Sentuhan Kaki
Baca juga: Harga Emas Naik 17/11/2025 - Emas Perhiasan Jambi Rp7,8 Juta per Mayam, Antam Rp2.351.000 per Gram
| Kejari Tebo Terima Uang Titipan 2 Perkara Tipikor yang Sedang Disidangkan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Kejaksaan-Negeri-Kejari-Tebo-menerima-uang-titipan-terkait-perkara.jpg)
|
|---|
| Tetap Santai Dihina, Kaesang Pangarep Samakan PSI dengan Gajah: Kita Ini Kuat! |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Ketua-Umum-PSI-Kaesang-Pangarep-1711.jpg)
|
|---|
| Diduga Hindari Truk CPO, Minibus Nyungsep di Perbatasan Mendalo-Simpang Rimbo Jambi |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/17112025-kecelakaan.jpg)
|
|---|
| Kronologi Penemuan Motor di Sungai Batanghari Jambi: Berkat Air Surut dan Sentuhan Kaki |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/20251117-Penemuan-motor-NMAX-di-Sungai-Batanghari-Jambi-viral.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/17112025-Ade-Novia-Maulana.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Kejari-Tebo-telah-menerima-berkas-dan-tersangka-pembunuhan-Imam-Komaini-Sidiq.jpg)






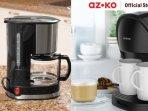

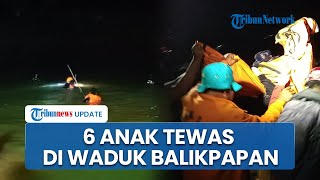
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/17112025-razia-kendaraan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Logo-PAN-atau-Partai-Amanat-Nasional.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Foto-Temenggug-kiri-dan-Temenggung-Jhon-kanan-dua-tokoh-adat-SAD-Merangin.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Pemerintah-Kota-Pemkot-Jambi-kembali-melakukan-pendataan-pedagang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/alat-berat-dikerahkan-untuk-pencarian-korban-peti-di-merangin-jambi-rabu-25122019.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.